B. Neo Evolusi
Gagasan dari neo evolusi
hampir sama dengan teori modernisasi. Neo evolusi menggunakan konteks histori
dalam membedah masyarakat tradisional dan modern, teori ini menyatakan
masyarakat modern lambat laun akan terjadi dari tahap tradisional melalui
proses diferensisasi sosial. Misalnya dalam masyarakat tradisional fungsi ekonomi,
politik, dan pendidikan dijalankan dibawah satu intstitusi saja, sedangkan dalam
masyarakat modern antara struktur sosial
dan organisasi harus dipisahkan untuk menjalankan fungsi politik, ekonomi, dan pendidikan.
Secara singkatnya, masyarakat mengubah struktur masyarakat sederhana menjadi lebih
kompleks dengan adanya stratifikasi kerja. Disebut neo evolusionisme dikarenakan
teori ini menentang pandangan teori evolusionisme yang menyatakan bahwa masyarakat
tradisional akan berkembang dengan satu arah (unilinear) menuju masyarakat
modern. Para ahli neo evolusionisme beranggapan banyak jalur yang dapat ditempuh
untuk menuju masyarakat modern seperti jalan kapitalis melalui demokrasi plural
yang terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 1950-an dan 1960-an teori-teori fungsionalis
seperti modernisasi dan neo evolusionisme sangat dominan.
Evolusi harus dikaji secara
ilmiah ketimbang secara spekulatif dengan memperhatikan semua kritik terhadap evolusionisme
klasik dan semua temuan sosial terbaru, termasuk temuan sosiologi sendiri. Keyakinan
ini membuat neo evolusionisme meninggalkan evolusionisme. Pergeserannya adalah sebagai
berikut:
1. Pusat perhatian bergeser
dari evolusi masyarakat global sebagai satu kesatuan ke proses yang muncul dalam
kesatuan sosial yang lebih terbatas seperti peradaban, kultur kesatuan masyarakat
yang terpisah seperti suku, Negara, bangsa, dan sebagainya.
2. Sasaran perhatian utama adalah
mekanisme penyebab evolusi ketimbang rentetan tahap perkembangan yang mesti dilalui.
Dengan kata lain, yang hendak di cari adalah “penjelasan”, bukan skema tipologi.
3. Analisis evolusi dirumuskan
secara deskriptif, kategoris menghindarkan penilaian dan isyarat tentang kemajuan.
“Bagi teoritisi neo evolusionisme, evolusi sosio-kultural berarti jauh lebih terbatas,
tak mengandung pertimbangan moral”.
4. Proporsi diungkap dalam peluang
ketimbang secara pasti.
5. Terjadi penggabungan bertahap
gagasan dari cabang evolusionisme lain seperti evolusionisme biologis yang
telah berkembang luas dan bebas yang menghasilkan banyak temuan dalam ilmu biologi.
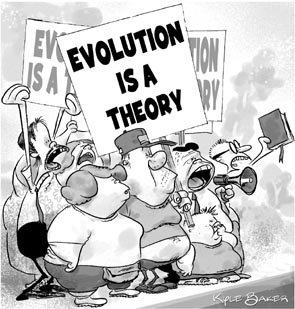


.jpg)




.jpg)









